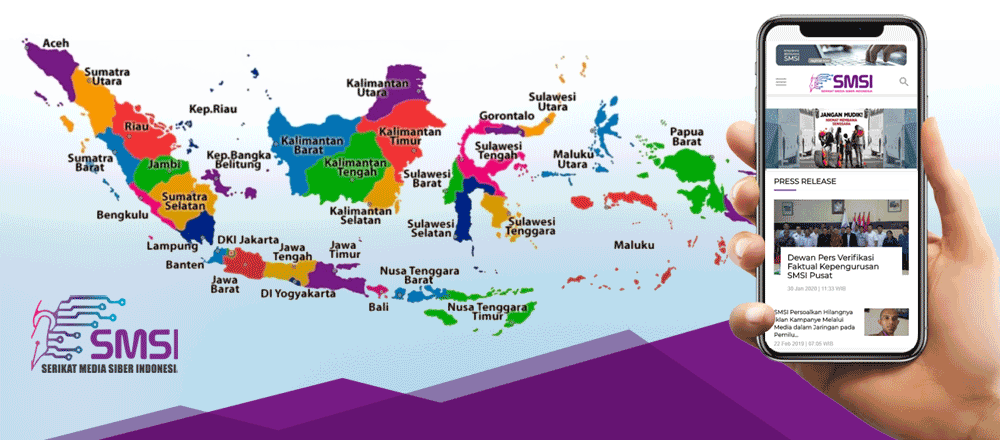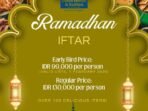Kenapa Reformasi UMKM Tak Bisa Lagi Ditunda?
Di tengah gelombang perubahan yang tengah mengguncang sektor keuangan nasional, publik menyaksikan satu hal yang semakin jarang terlihat dalam politik kebijakan: ketegasan yang dibangun di atas data, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan eksekusi yang cepat.
Itulah kesan yang muncul ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah berani menggelontorkan likuiditas Rp200 triliun untuk memompa kredit perbankan, sembari menegakkan disiplin di tubuh otoritas fiskal dan perpajakan. Dalam hitungan minggu, kehadirannya memberi sinyal bahwa negara serius memperbaiki fondasi ekonomi.
Pertanyaannya: mengapa energi kepemimpinan semacam ini tidak kita lihat secara setara di sektor UMKM—sektor yang justru menopang lebih dari separuh perekonomian Indonesia?
UMKM menyumbang 61% PDB, 97% lapangan kerja, dan menjadi basis ekonomi mayoritas keluarga Indonesia. Namun kontribusi besar ini tidak berbanding lurus dengan terobosan kebijakan yang mereka terima.
Ekosistem UMKM selama bertahun-tahun berjalan seperti mesin besar yang digerakkan oleh program-program kecil: pelatihan, pendampingan, bantuan peralatan, pameran, dan klasterisasi.
Semuanya penting, tetapi tidak ada yang bersifat game changer. Sektor raksasa ini justru dikelola dengan pendekatan yang aman, konservatif, dan terlalu administratif.
Karena itu, gagasan membawa “roh” Purbaya ke Kementerian UMKM bukan soal mengganti orang, tetapi membawa model kepemimpinan yang mampu mengguncang struktur lama. UMKM membutuhkan filsafat kebijakan yang sama: berani, teknokratis, dan berorientasi pada dampak, bukan seremoni.
Pertama, UMKM membutuhkan shock therapy struktural, bukan sekadar workshop atau seremoni kemitraan. Beban sebenarnya UMKM berada di tiga titik: pembiayaan terjangkau, akses pasar yang adil, dan proteksi terhadap dominasi oligopoli di ritel maupun distribusi.
Semua ini hanya dapat ditangani oleh menteri yang punya keberanian politik dan kapasitas teknis. Sosok yang mampu memaksa ekosistem perbankan menyalurkan kredit tanpa membuatnya terjebak prosedur.
Sosok yang berani menegakkan aturan ke platform digital dan ritel modern agar memberi ruang yang lebih adil bagi produk kecil dan menengah. Sosok yang dapat memimpin audit besar-besaran terhadap kebijakan koperasi dan lembaga pembiayaan untuk memastikan tidak ada kebocoran atau ketidaktepatan sasaran.
Pendek kata: UMKM membutuhkan lompatan struktural yang tidak bisa dicapai jika kepemimpinannya tetap berorientasi pada program kecil dan aman secara politik.
Kedua, UMKM membutuhkan keberanian mengambil risiko yang ditopang data, seperti yang dilakukan Purbaya di sektor keuangan. Dalam sektor UMKM, keberanian ini berarti menyiapkan kebijakan yang mungkin tidak populer: menghapus biaya-biaya yang mencekik pelaku usaha kecil, menetapkan kewajiban kuota rak UMKM di ritel modern, membatasi termin pembayaran yang terlalu panjang, hingga memaksa transparansi rantai pasok.
Ini semua mensyaratkan kepemimpinan tipe teknokrat militan—yang bersedia bertarung demi keadilan ekonomi.
Model Purbaya menunjukkan bahwa publik siap menerima kebijakan keras ketika tujuannya jelas dan basis datanya kuat. UMKM membutuhkan pendekatan yang sama.
Ketiga, UMKM membutuhkan pemimpin yang mampu mengeksekusi, bukan hanya mengimbau. Selama ini banyak kebijakan UMKM bersifat rekomendatif: “mendorong,” “mengajak,” “mengimbau,” “mengupayakan.” Padahal relasi UMKM dengan pasar modern bersifat asimetris dan tidak bisa diselesaikan dengan imbauan moral.
Dibutuhkan menteri yang dengan tegas memerintahkan audit, menerapkan insentif dan disinsentif, serta mengubah pasar melalui kebijakan yang memaksa bukan sekadar memotivasi.
Energi seperti inilah yang membuat publik merasa Purbaya “menggerakkan” negara, bukan sekadar memimpin kementerian. Dan energi serupa sangat dibutuhkan oleh jutaan pelaku UMKM yang selama ini berjalan sendiri dalam kegelapan pasar yang tidak bersahabat.
Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan pelaku UMKM yang kuat, pekerja keras, dan inovatif. Yang kurang adalah kebijakan yang berani bertarung untuk mereka. Jika sektor keuangan saja bisa direformasi dalam hitungan minggu oleh seorang pemimpin teknokratis yang tegas, mengapa sektor UMKM—yang menopang hidup rakyat banyak—tidak mendapatkan energi kepemimpinan yang sama?
Saat ini, UMKM butuh sosok bertipe Purbaya: pemimpin yang tidak takut konflik, berorientasi hasil, dan bersedia mengubah ekosistem dengan cara yang nyata, bukan simbolik.
Tanpa keberanian seperti itu, UMKM akan terus menjadi slogan besar dengan hasil kecil. Dengan keberanian seperti itu, UMKM dapat menjadi kekuatan ekonomi yang benar-benar mengangkat kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas 2045.
Riskal Arief
Pengurus DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan_